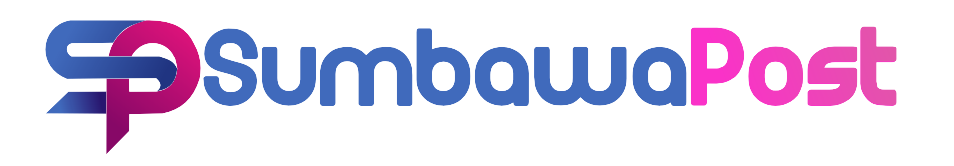Oleh: Rusdiansyah (Advocates And Legal Consultants )
PEMBERDAYAAN kini menjadi mantra pembangunan. Hampir setiap kebijakan pemerintah menyelipkan kata itu, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan perempuan, hingga pemberdayaan desa. Tapi mari kita bertanya dengan jujur, apakah yang disebut berdaya itu benar-benar berdaya, atau sekadar menjadi objek yang diatur agar tampak berdaya?
Program Desa Berdaya yang kini digaungkan di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu gagasan progresif. Ia berbicara tentang penguatan fondasi pembangunan desa dengan prinsip transformasi, inovasi, kolaborasi, dan orkestrasi. Pemerintah menjadi dirigen yang mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah desa, mulai dari air bersih, kemiskinan, hingga stunting.
Gagasannya indah, narasinya kuat. Tapi justru di situlah letak ujian sebenarnya. Sebab, kolaborasi sejati bukan hanya persoalan koordinasi antar-lembaga, tetapi tentang siapa yang memegang kendali dalam menentukan arah perubahan.
Apakah masyarakat Desa menjadi pelaku utama, atau justru masih menjadi penonton dalam simfoni besar bernama pembangunan? Dalam teori community empowerment yang dikemukakan Robert Chambers, bahwa pemberdayaan menuntut putting the last first yaitu menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat. Namun dalam banyak praktik, kolaborasi sering bergeser menjadi koordinasi sepihak, di mana pemerintah tetap menjadi pusat kontrol dan masyarakat hanya mengikuti alur yang telah ditentukan.
Di sinilah kontradiksi halus itu muncul dimana Desa Berdaya ingin meng orkestrasi kolaborasi, tapi terlalu banyak tangan pemerintah yang masih mengatur ritmenya. Padahal, desa yang benar-benar berdaya tidak menunggu aba-aba dari atas. Mereka menciptakan nadanya sendiri, dimana mereka mengatur harmoni pembangunan sesuai konteks sosial, budaya, dan potensi lokal mereka.
Program ini mengusung 20 tema desa, mulai dari Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tangguh Bencana, Desa Inklusi (GEDSI), hingga Desa Wisata Maju. Slogan-slogan ini menggugah imajinasi publik. Namun secara ilmiah, pemberdayaan tidak dapat dibangun dari tema yang luas tanpa indikator yang terukur.
Apakah ada baseline data yang jelas untuk tiap tema? Bagaimana mengukur keberhasilan Desa Bebas Narkoba atau Desa Literasi? Tanpa kerangka evaluasi partisipatif, semua program rawan menjadi ceremonial development, penuh spanduk dan publikasi, tapi minim transformasi struktural.
Dalam pendekatan participatory rural appraisal (PRA), masyarakatlah yang seharusnya mendefinisikan apa arti ‘Berdaya’ bagi mereka. Sebab pemberdayaan yang dipaksakan dari luar hanya akan melahirkan ketergantungan baru yaitu masyarakat tampak aktif di permukaan, namun pasif dalam pengambilan keputusan.
Kunci keberhasilan program pemberdayaan bukan pada jumlah pelatihan, tetapi pada kualitas partisipasi. Sayangnya, dalam banyak program, partisipasi sering berhenti di level formalitas dimana masyarakat hadir dalam rapat, tanda tangan daftar hadir, lalu menunggu bantuan turun. Padahal, partisipasi sejati bersifat transformasional, membangkitkan kesadaran kritis warga untuk memahami struktur sosial yang mengekang mereka, sebagaimana diajarkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed.
Pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator kesadaran, bukan hanya penyedia proyek. Pendamping desa bukan sekadar birokrat lapangan, melainkan agen perubahan sosial yang membantu masyarakat merefleksikan masalahnya, menemukan solusinya, dan bergerak bersama secara mandiri.
Program Desa Berdaya menekankan keunggulan pada hilirisasi, industrialisasi, dan pariwisata. Secara ekonomi, ini strategis. Namun dari perspektif ecological empowerment, fokus yang berlebihan pada industrialisasi dapat mengikis identitas sosialekologis desa. Pembangunan yang terlalu bertumpu pada pasar sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan dan relasi sosial yang menjadi nadi kehidupan desa.
Kita tidak ingin melihat desa yang maju secara statistik tetapi kehilangan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kearifan ekologis yang menjadi modal sosial bangsa ini.
Desa berdaya sejati bukanlah desa yang kaya secara material semata, tetapi desa yang mampu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Rasanya menyampaikan kritik konstruktif tampa solusi seperti lentera yang menyorot
gelap, tapi tak menunjukkan jalan keluar, maka untuk menjadikan Desa Berdaya lebih bermakna dan berkelanjutan, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:
1. Reorientasi peran pemerintah yaitu dari pengarah utama menjadi fasilitator keswadayaan. Biarkan masyarakat menentukan prioritas, pemerintah mendukung
prosesnya.
2. Penguatan basis data sosial dimana setiap tema desa harus berangkat dari social mapping partisipatif agar intervensi tepat sasaran.
3. Pendidikan kesadaran kritis (critical awareness) dengan melibatkan masyarakat dalam refleksi sosial, agar partisipasi mereka bukan sekadar administratif, melainkan ideologis dan emosional.
4. Integrasi nilai ekologis dan kultural, kita mendorong pembangunan harus berbasis keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal, bukan sekadar ekonomi.
5. Evaluasi partisipatif dan terbuka, langkah ini harus dilakukan karna setiap capaian harus dievaluasi bersama warga, bukan hanya dilaporkan ke pusat. Desa yang berdaya tidak lahir dari proyek, tetapi dari kesadaran.
Desa yang kuat bukan karena banyaknya bantuan, tetapi karena warganya percaya bahwa kekuatan itu telah lama mereka miliki. Pemerintah boleh menjadi orkestrator, tetapi suara terindah tetap milik rakyat desa sendiri, karena mereka yang paling tahu irama kehidupan di tanah mereka. Desa Berdaya sejati bukan tentang desa yang diatur untuk kuat, tetapi desa yang sadar bahwa ia sudah kuat. Yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk membuktikannya.